Kambing dan Hujan
 |
| Sampul |
Pengarang : Mahfud Ikhwan
Penerbit : Bentang Pustaka
Tahun : 2015
Dibaca : 1 September 2015
Rating : ★★★★
Tahun : 2015
Dibaca : 1 September 2015
Rating : ★★★★
Aku mulai dari embel-embel Pemenang Pertama Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014 yang terdapat pada sampul buku dan membuatku tidak pikir dua kali untuk beli. Saking menyenangkan dan tersihir membaca buku ini, yang pada awalnya aku hanya beli versi ebook, aku membeli juga versi fisiknya. Entahlah, kalau tak melihat secara konkret bentuk bukunya, aku serasa tidak pernah membaca buku ini. Kasus seperti ini pula yang menimpa Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Bibli selalu mengomel tentang hal ini. Buruk sekali diri ini.
Kembali pada buku yang ditulis pengarang pada 2013 ini. Aku bisa bilang bahwa buku ini memang berat dan mengambil bahasan yang sensitif. Kenapa? Tahu dua organisasi Islam di Indonesia yang sangat berbeda dalam tata cara ibadah serta sunah-sunah yang dianut dan diamalkan. Pengarang benar-benar mengambil perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Semua itu diramu sebagai dasar konflik yang dialami oleh para tokoh di dalamnya. Sungguh berani!
Mif dan Fauzia benar-benar ngebet menikah. Bahkan keduanya berniat kawin lari karena hubungan mereka digantung oleh orangtua masing-masing. Sebenarnya bukan masalah karena kedua orangtua mereka sama-sama pemuka agama di desa. Masalahnya mereka menganut paham yang berbeda. Yang satu Nahdliyin, satu lagi Pembaharu.
Mif dan Fauzia berusaha dengan berbagai cara; meyakinkan orangtua masing-masing untuk memberikan restu—hal terpenting untuk memulai. Hingga mereka tahu bahwa kedua ayahnya, Pak Kandar (bapaknya Mif) dan Pak Fauzan (bapaknya Fauzia) dulunya adalah sahabat dekat. Sangat dekat, bahkan karib. Bagaimana bisa dua sahabat yang menghabiskan masa kecil bersama di Gumuk Genjik dan menggembala kambing bersama, menjadi saling berkubu?
Seperti yang kubilang di atas, penulis sungguh berani mengangkat isu sosial dan agama yang sangat sensitif menjadi bahan cerita. Aku dibawa melalui mesin waktu ketika berpacaran—diam kau, Bibli!—dengan gadis yang adalah anak dari—bisa dibilang—pemuka agama di lingkungannya. Hingga mengetahuiku tidak melakukan tradisi keagamaan yang dianutnya, beberapa hari setelahnya aku tiba-tiba dikabari bahwa hubungan kami (aku dan dia) harus berakhir karena perbedaan prinsip. Awalnya aku ragu kenapa begitu langsung, mengingat tidak ada masalah apa pun dengan hubungan yang sedang kami jalani—kecuali kalau hubungan jarak jauh yang sudah lama kami lalui itu adalah masalah.
Aku memang lahir di keluarga yang agamanya lumayan diperhatikan—alhamdulillaah. Almarhum kakek yang waktu itu menjabat Kepala Ranting Cabang Muhammadiyah sangat disegani. Aku dididik dengan ajaran sholat yang tanpa perlu hapalan niat. Aku juga diajari untuk sholat tarawih empat rakaat satu kali salam. Tentu saja hal itu sudah mendarah daging di tubuhku. Tapi aku tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa berdampak pada kehidupanku selanjutnya; dengan gadis itu misalnya.
Istilah "kambing dan hujan" juga baru aku tahu. Buku ini menjelaskan maksudnya. Kambing tidak suka air, apalagi dengan hujan yang merupakan laskar air. Itu berarti kambing dan hujan tidak bakal bersatu. Keduanya hampir mustahil dipertemukan. Istilah ini jugalah yang penulis beri kepada Pak Kandar dan Pak Fauzan. Bagaimana dulunya mereka adalah dua karib bagai amplop dengan prangko. Bagaimana keduanya menemukan perbedaan di antara masing-masing. Bagaimana keduanya saling menjauh dan makin menjauh bagai kutub Utara dan Selatan. Bagaimana tingkah keduanya memberi dampak yang besar bagi anak-anak mereka—Mif dan Fauzia.
Akhir kata, buku ini memberikan angin keberanian yang mengangkat bagian paling sensitif masyarakat. Terlepas dari alur waktu cerita yang njelimet—karena present tense disusupi berbagai macam past tense—aku tetap mengusungkan buku ini sebagai buku karya anak bangsa terbaik yang kubaca sejauh 2015 ini. Aku tentu saja merekomendasikan buku ini kepada kalian yang sangat kental dengan agamanya. Aku juga merekomendasikan buku ini kepada kalian yang ingin tahu Islam dan njelimet-nya Islam di Indonesia. Tidak lupa, aku juga merekomendasikan buku ini kepada kalian yang suka kisah roman kontemporer, karena buku ini sungguh berbeda dari roman-roman yang terbit akhir-akhir ini.
Ulasan ini untuk tantangan: 100 Hari Membaca Satra Indonesia.
Masuk dalam Buku Paling Raafi Kenang pada 2015.
Kembali pada buku yang ditulis pengarang pada 2013 ini. Aku bisa bilang bahwa buku ini memang berat dan mengambil bahasan yang sensitif. Kenapa? Tahu dua organisasi Islam di Indonesia yang sangat berbeda dalam tata cara ibadah serta sunah-sunah yang dianut dan diamalkan. Pengarang benar-benar mengambil perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Semua itu diramu sebagai dasar konflik yang dialami oleh para tokoh di dalamnya. Sungguh berani!
Mif dan Fauzia benar-benar ngebet menikah. Bahkan keduanya berniat kawin lari karena hubungan mereka digantung oleh orangtua masing-masing. Sebenarnya bukan masalah karena kedua orangtua mereka sama-sama pemuka agama di desa. Masalahnya mereka menganut paham yang berbeda. Yang satu Nahdliyin, satu lagi Pembaharu.
Mif dan Fauzia berusaha dengan berbagai cara; meyakinkan orangtua masing-masing untuk memberikan restu—hal terpenting untuk memulai. Hingga mereka tahu bahwa kedua ayahnya, Pak Kandar (bapaknya Mif) dan Pak Fauzan (bapaknya Fauzia) dulunya adalah sahabat dekat. Sangat dekat, bahkan karib. Bagaimana bisa dua sahabat yang menghabiskan masa kecil bersama di Gumuk Genjik dan menggembala kambing bersama, menjadi saling berkubu?
***
Seperti yang kubilang di atas, penulis sungguh berani mengangkat isu sosial dan agama yang sangat sensitif menjadi bahan cerita. Aku dibawa melalui mesin waktu ketika berpacaran—diam kau, Bibli!—dengan gadis yang adalah anak dari—bisa dibilang—pemuka agama di lingkungannya. Hingga mengetahuiku tidak melakukan tradisi keagamaan yang dianutnya, beberapa hari setelahnya aku tiba-tiba dikabari bahwa hubungan kami (aku dan dia) harus berakhir karena perbedaan prinsip. Awalnya aku ragu kenapa begitu langsung, mengingat tidak ada masalah apa pun dengan hubungan yang sedang kami jalani—kecuali kalau hubungan jarak jauh yang sudah lama kami lalui itu adalah masalah.
Aku memang lahir di keluarga yang agamanya lumayan diperhatikan—alhamdulillaah. Almarhum kakek yang waktu itu menjabat Kepala Ranting Cabang Muhammadiyah sangat disegani. Aku dididik dengan ajaran sholat yang tanpa perlu hapalan niat. Aku juga diajari untuk sholat tarawih empat rakaat satu kali salam. Tentu saja hal itu sudah mendarah daging di tubuhku. Tapi aku tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa berdampak pada kehidupanku selanjutnya; dengan gadis itu misalnya.
Istilah "kambing dan hujan" juga baru aku tahu. Buku ini menjelaskan maksudnya. Kambing tidak suka air, apalagi dengan hujan yang merupakan laskar air. Itu berarti kambing dan hujan tidak bakal bersatu. Keduanya hampir mustahil dipertemukan. Istilah ini jugalah yang penulis beri kepada Pak Kandar dan Pak Fauzan. Bagaimana dulunya mereka adalah dua karib bagai amplop dengan prangko. Bagaimana keduanya menemukan perbedaan di antara masing-masing. Bagaimana keduanya saling menjauh dan makin menjauh bagai kutub Utara dan Selatan. Bagaimana tingkah keduanya memberi dampak yang besar bagi anak-anak mereka—Mif dan Fauzia.
Akhir kata, buku ini memberikan angin keberanian yang mengangkat bagian paling sensitif masyarakat. Terlepas dari alur waktu cerita yang njelimet—karena present tense disusupi berbagai macam past tense—aku tetap mengusungkan buku ini sebagai buku karya anak bangsa terbaik yang kubaca sejauh 2015 ini. Aku tentu saja merekomendasikan buku ini kepada kalian yang sangat kental dengan agamanya. Aku juga merekomendasikan buku ini kepada kalian yang ingin tahu Islam dan njelimet-nya Islam di Indonesia. Tidak lupa, aku juga merekomendasikan buku ini kepada kalian yang suka kisah roman kontemporer, karena buku ini sungguh berbeda dari roman-roman yang terbit akhir-akhir ini.
"Alangkah baiknya suami istri itu saling mencintai. Namun, saling mencintailah dengan cara yang biasa dan sederhana, jangan terlalu menggebu, apalagi membabi buta. Jangan sampai punya pandangan 'tanpa dirimu di sisiku lebih baik aku mati' atau 'hidupku tak berarti tanpamu'. Jangan begitu. Janganlah meniru tokoh-tokoh dalam roman Hamka—kalian berdua membaca Hamka, bukan? Coba cermati, karena cinta yang terlalu menggebu-gebu, mereka rata-rata mati muda. Hampir semuanya." (hal. 362)
Ulasan ini untuk tantangan: 100 Hari Membaca Satra Indonesia.
Masuk dalam Buku Paling Raafi Kenang pada 2015.

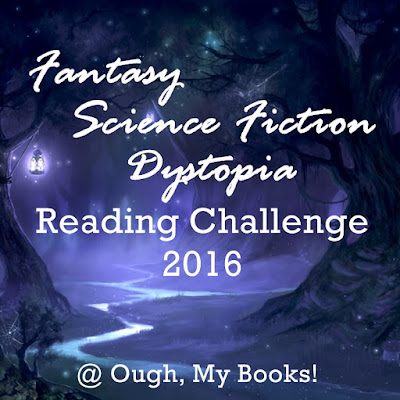

aku kok jadi penasaran, akhir-akhir ini senang melirik buku sastra :)
BalasHapus