A Reason to Stay Alive: Pulang
 |
| Edited by Me |
Setiap orang punya masa paling berat dalam hidupnya. Mungkin sekitar Januari tahun lalu, seorang teman yang kukenal dari komunitas buku menghubungiku untuk bertemu. Kami pernah dekat tetapi kehadirannya kala itu berbeda. Dia mengatakan ada masalah dengan semua orang; pacarnya mengekangnya, ayahnya dalam keadaan sakit keras yang tak bisa membuat beliau melakukan aktivitas, ibunya selalu memintanya uang padahal segala yang dia punya telah diserahkan, belum lagi masalah pekerjaannya. Dia meracau, lalu menangis setelahnya. Dia bahkan sempat mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Aku yang kala itu merasa hidupku tidak ada apa-apanya hanya bisa mendengarkan—membiarkan dirinya mengeluarkan segala yang ingin dikeluarkannya. Dia kebingungan dan kerap tiba-tiba diam di sela-sela curhatannya—dua tanda depresi yang aku tahu sebagai orang awam.
Dia terus menghubungiku dan meminta bertemu. Awalnya, aku merasa risih karena aku pernah punya rasa padanya dan aku ingin menguburnya. Aku juga punya prioritas lain yang perlu diurusi. Namun, aku bertanya dalam hati: Bagaimana kalau aku berada dalam posisinya? Mungkin cuma aku yang dibutuhkannya saat itu dan menceritakan semuanya dari awal lagi kepada orang lain sungguh melelahkan. Meluluhkan ego, aku menerima untuk terus berhubungan dengannya. Kadang kami bertemu selepas jam kantor, kadang kami bertemu saat akhir pekan—pernah suatu hari kami menghabiskan waktu seharian penuh mengunjungi Perpusnas dan Monas. Aku kemudian muncul dengan pemikiran bahwa berada di sampingnya cukup untuk menghilangkan rasa depresinya walau barang sejenak.
Aku tahu, aku tahu. Aku sok tahu tentang dia yang mungkin depresi. Kala itu, aku tidak bilang padanya bahwa dia depresi—demi Tuhan, siapa aku bisa mendiagnosis seseorang memiliki “sesuatu”. Aku cuma bilang dia mungkin sedang berada dalam masa-masa terberatnya—masa terkelamnya. Aku hanya bersabar menemaninya—cuma itu yang kulakukan. Dan, hei, itu salah satu dari daftar bagaimana bersanding dengan seseorang yang menderita depresi atau kecemasan dalam “Reasons to Stay Alive” karya Matt Haig. Buku yang membuatku lebih paham tentang depresi dan kecemasan.
Kutipan di atas berada di urutan 8 dari daftar bagaimana bersanding dengan seseorang yang menderita depresi atau kecemasan dalam “Reasons to Stay Alive” karya Matt Haig. Bisa dibilang, buku ini termasuk buku yang membesarkan namanya. Haig berani menyampaikan pengalaman depresinya secara rinci dalam buku itu. Dia mengawali kisahnya dengan deskripsi ketika dia berada di Ibiza bersama pacarnya Andrea dan merasakan hal “aneh”—bukan sesuatu yang berhubungan dengan fisik, tetapi berhubungan dengan pikiran. Dia lalu bercerita tentang tanda-tanda depresi yang semakin hari semakin menggerogotinya. Yang paling personal dari pengalamannya adalah percakapan antara dirinya yang sekarang dengan dirinya yang dulu alias dirinya yang sedang dalam masa terkelamnya.
Dalam “Reasons to Stay Alive”, Haig juga memberikan saran-saran yang diambil dari pengalamannya sendiri maupun dari sumber-sumber tepercaya—ala self-help book kepada penderita depresi dan kecemasan sekaligus pembaca pada umumnya. Daftar bagaimana bersanding dengan seseorang yang menderita depresi atau kecemasan (halaman 119) adalah salah satunya. Ada juga daftar hal-hal yang depresi akan katakana padamu (halaman 51), daftar tokoh terkenal yang menderita depresi (halaman 159), sampai daftar twit dengan tagar #reasonstostayalive (halaman 202). Bagian tentang daftar-daftar ini sebetulnya menarik; pembaca jadi mendapat wawasan yang lebih tentang depresi dan hal-hal yang berkutat di sekitarnya.
Namun, aku merasa penggabungan antara pengalaman personal, saran-saran ala self-help book, dan daftar-daftar "hal-hal" yang membuatnya seperti ikhtisar itu tidak nyaman. Saat membaca bukunya, aku menemukan bahwa pada satu bab Haig menarasikan pengalamannya tentang depresi, lalu bab selanjutnya berubah menjadi daftar bentuk-bentuk depresi. Itu yang menurutku mengganggu. Mungkin buku ini adalah terbobosan, seperti yang dikatakan Haig dalam kata pengantar: “this book is a mixture of a memoir, a self-help book, and an overview.” Namun, aku bisa bilang bahwa itu terlalu dipaksakan. Andai saja, Haig hanya bercerita tentang kisahnya saja. Secara keseluruhan, buku ini lebih pada "membantu" tidak hanya orang-orang yang mengalami depresi dan kecemasan tetapi juga orang-orang yang ingin membantu mereka. Jadi, masuk kategori self-help, ya!
Omong-omong soal masa terkelam, mungkin tinggal di Amerika Serikat adalah masa terkelamku. Tidak. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak menikmati pengalaman yang diberikan oleh Sang Pemberi Kesempatan ini. Namun, ada hal lain yang tidak aku ekspektasikan sebelumnya. Aku tidak ada persiapan apa pun untuk mengikuti program beasiswa yang membawaku ke Amerika Serikat ini. Aku hanya mengirimkan esai lamaran dan mengikuti prosedur seleksi—dari wawancara, tes kesehatan, membuat visa Amerika Serikat, sampai siap berangkat. Aku pikir aku sudah siap fisik dan mental, sampai aku tiba di sini dan mengetahui bagaimana dan dengan siapa aku tinggal. Dan itu … sungguh di luar kontrolku.
Dalam program ini, peserta akan tinggal di sebuah apartemen bersama peserta lainnya. Yang menarik adalah peserta-peserta yang tinggal dalam satu apartemen harus dari negara partisipan yang berbeda. Awalnya, aku antusias dengan hal ini: hidup bersama peserta dari negara lain dan berbagi pengalaman serta kultur. Sampailah pada fakta aku luput bahwa setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda, apalagi dari negara yang berbeda. Sialnya, aku tinggal bersama mereka yang tidak bersih dan selalu menelepon keluarganya di negaranya. Tidak, biar aku keluarkan saja: (1) yang satu suka masak tetapi tidak pernah membersihkan langsung peralatan masaknya setelahnya dan (2) yang satu lain menelepon tanpa kenal waktu—dari pagi sampai malam sampai pagi lagi—dan dengan suara yang lantang.
Jangan tanya betapa aku sudah berusaha menyampaikan keberatanku kepada mereka. Aku sudah melakukan berbagai cara: meminta mereka baik-baik, berkeluh kesah kepada koordinator, bertemu konselor bersama dengan semua penghuni apartemen. Hasilnya: nol besar. Mereka terus dan akan melakukannya lagi dan lagi karena itu “kebiasaan”.
Pada akhirnya, aku yang mengalah. Aku mulai terbiasa menggunakan penutup telinga setiap pergi tidur. Aku akan beranjak ke apartemen peserta lain untuk melakukan kegiatanku: seperti menulis dan membaca. Aku juga menjanjikan diri untuk tidak pernah menggunakan dapur di apartemen sendiri selain untuk mengisi air minum atau mencuci perkakas. Pada satu titik, aku sungguh ingin “mengakhiri” ini (lihat tanda kutip itu?). Aku pernah berpikir untuk meminum pil tidur agar mudah tidur. Aku berpikir yang tidak-tidak agar aku bisa segera hengkang dari apartemen itu, bahkan sampai saat ini. Sungguh 2018 yang penuh kejutan!
Sudah tahun baru. Alasan untuk hidupku cuma satu: segera mengakhiri program ini dan pulang ke Indonesia. Bekerja, membaca buku, menulis, makan nasi bebek—hal-hal yang kurindukan. Dan yang paling kuidam-idamkan saat ini cuma satu: tinggal sendiri di tempat yang sepi dan kondusif. Aku muak, sungguh. Aku bahkan bertanya-tanya kenapa aku melakukan ini; pergi ke sini. Terlepas dari itu, aku bisa bilang bahwa mungkin ini adalah masa terkelamku dan aku harus bertahan serta bersabar. Sama seperti yang disampaikan Haig dalam bukunya tentang daftar bagaimana bersanding dengan seseorang yang menderita depresi atau kecemasan, tepatnya nomor 8. Bedanya, aku adalah si seseorang itu. This too shall pass, anyway! Selamat tahun baru!
Catatan:
Tahun : 2016
Dibaca : 29 Desember 2018
Rating : ★★★
Rating : ★★★
“Be patient. Understand it isn’t going to be say. Depression ebbs and flows and moves up and down. It doesn’t stay still. Do not take one happy/bad moment as proof of recovery/relapse. Play the long game.”
Kutipan di atas berada di urutan 8 dari daftar bagaimana bersanding dengan seseorang yang menderita depresi atau kecemasan dalam “Reasons to Stay Alive” karya Matt Haig. Bisa dibilang, buku ini termasuk buku yang membesarkan namanya. Haig berani menyampaikan pengalaman depresinya secara rinci dalam buku itu. Dia mengawali kisahnya dengan deskripsi ketika dia berada di Ibiza bersama pacarnya Andrea dan merasakan hal “aneh”—bukan sesuatu yang berhubungan dengan fisik, tetapi berhubungan dengan pikiran. Dia lalu bercerita tentang tanda-tanda depresi yang semakin hari semakin menggerogotinya. Yang paling personal dari pengalamannya adalah percakapan antara dirinya yang sekarang dengan dirinya yang dulu alias dirinya yang sedang dalam masa terkelamnya.
Dalam “Reasons to Stay Alive”, Haig juga memberikan saran-saran yang diambil dari pengalamannya sendiri maupun dari sumber-sumber tepercaya—ala self-help book kepada penderita depresi dan kecemasan sekaligus pembaca pada umumnya. Daftar bagaimana bersanding dengan seseorang yang menderita depresi atau kecemasan (halaman 119) adalah salah satunya. Ada juga daftar hal-hal yang depresi akan katakana padamu (halaman 51), daftar tokoh terkenal yang menderita depresi (halaman 159), sampai daftar twit dengan tagar #reasonstostayalive (halaman 202). Bagian tentang daftar-daftar ini sebetulnya menarik; pembaca jadi mendapat wawasan yang lebih tentang depresi dan hal-hal yang berkutat di sekitarnya.
Namun, aku merasa penggabungan antara pengalaman personal, saran-saran ala self-help book, dan daftar-daftar "hal-hal" yang membuatnya seperti ikhtisar itu tidak nyaman. Saat membaca bukunya, aku menemukan bahwa pada satu bab Haig menarasikan pengalamannya tentang depresi, lalu bab selanjutnya berubah menjadi daftar bentuk-bentuk depresi. Itu yang menurutku mengganggu. Mungkin buku ini adalah terbobosan, seperti yang dikatakan Haig dalam kata pengantar: “this book is a mixture of a memoir, a self-help book, and an overview.” Namun, aku bisa bilang bahwa itu terlalu dipaksakan. Andai saja, Haig hanya bercerita tentang kisahnya saja. Secara keseluruhan, buku ini lebih pada "membantu" tidak hanya orang-orang yang mengalami depresi dan kecemasan tetapi juga orang-orang yang ingin membantu mereka. Jadi, masuk kategori self-help, ya!
***
Omong-omong soal masa terkelam, mungkin tinggal di Amerika Serikat adalah masa terkelamku. Tidak. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak menikmati pengalaman yang diberikan oleh Sang Pemberi Kesempatan ini. Namun, ada hal lain yang tidak aku ekspektasikan sebelumnya. Aku tidak ada persiapan apa pun untuk mengikuti program beasiswa yang membawaku ke Amerika Serikat ini. Aku hanya mengirimkan esai lamaran dan mengikuti prosedur seleksi—dari wawancara, tes kesehatan, membuat visa Amerika Serikat, sampai siap berangkat. Aku pikir aku sudah siap fisik dan mental, sampai aku tiba di sini dan mengetahui bagaimana dan dengan siapa aku tinggal. Dan itu … sungguh di luar kontrolku.
Dalam program ini, peserta akan tinggal di sebuah apartemen bersama peserta lainnya. Yang menarik adalah peserta-peserta yang tinggal dalam satu apartemen harus dari negara partisipan yang berbeda. Awalnya, aku antusias dengan hal ini: hidup bersama peserta dari negara lain dan berbagi pengalaman serta kultur. Sampailah pada fakta aku luput bahwa setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda, apalagi dari negara yang berbeda. Sialnya, aku tinggal bersama mereka yang tidak bersih dan selalu menelepon keluarganya di negaranya. Tidak, biar aku keluarkan saja: (1) yang satu suka masak tetapi tidak pernah membersihkan langsung peralatan masaknya setelahnya dan (2) yang satu lain menelepon tanpa kenal waktu—dari pagi sampai malam sampai pagi lagi—dan dengan suara yang lantang.
Jangan tanya betapa aku sudah berusaha menyampaikan keberatanku kepada mereka. Aku sudah melakukan berbagai cara: meminta mereka baik-baik, berkeluh kesah kepada koordinator, bertemu konselor bersama dengan semua penghuni apartemen. Hasilnya: nol besar. Mereka terus dan akan melakukannya lagi dan lagi karena itu “kebiasaan”.
Pada akhirnya, aku yang mengalah. Aku mulai terbiasa menggunakan penutup telinga setiap pergi tidur. Aku akan beranjak ke apartemen peserta lain untuk melakukan kegiatanku: seperti menulis dan membaca. Aku juga menjanjikan diri untuk tidak pernah menggunakan dapur di apartemen sendiri selain untuk mengisi air minum atau mencuci perkakas. Pada satu titik, aku sungguh ingin “mengakhiri” ini (lihat tanda kutip itu?). Aku pernah berpikir untuk meminum pil tidur agar mudah tidur. Aku berpikir yang tidak-tidak agar aku bisa segera hengkang dari apartemen itu, bahkan sampai saat ini. Sungguh 2018 yang penuh kejutan!
Sudah tahun baru. Alasan untuk hidupku cuma satu: segera mengakhiri program ini dan pulang ke Indonesia. Bekerja, membaca buku, menulis, makan nasi bebek—hal-hal yang kurindukan. Dan yang paling kuidam-idamkan saat ini cuma satu: tinggal sendiri di tempat yang sepi dan kondusif. Aku muak, sungguh. Aku bahkan bertanya-tanya kenapa aku melakukan ini; pergi ke sini. Terlepas dari itu, aku bisa bilang bahwa mungkin ini adalah masa terkelamku dan aku harus bertahan serta bersabar. Sama seperti yang disampaikan Haig dalam bukunya tentang daftar bagaimana bersanding dengan seseorang yang menderita depresi atau kecemasan, tepatnya nomor 8. Bedanya, aku adalah si seseorang itu. This too shall pass, anyway! Selamat tahun baru!
Catatan:
1. Aku sudah meminta izin untuk mengangkat kisah teman yang kukenal dari komunitas buku itu.
2. Aku siap menerima segala konsekuensi atas tayangnya pos ini. What's the worst thing could happen?


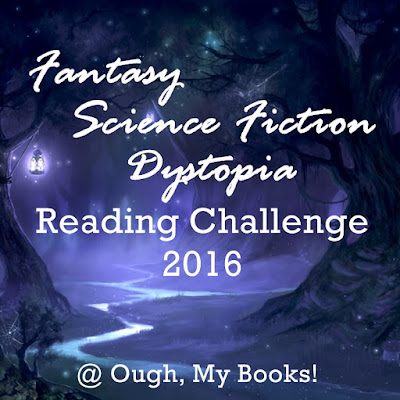

Komentar
Posting Komentar