Cerita dari Gurun: Setelah Mengunjungi Banyak Negara Bagian di Amerika Serikat
 |
| Edited by Me |
“They said there are two teams: team saving and team wasting. Team saving obviously think million times to spend money. Team wasting tend to do not care about money and take opportunities they are facing. I am the second.”
Pada salah satu pos Instagram-ku (yang sekarang sudah dienyahkan), aku sempat mengatakan di atas. Ya, memang sih, aku baru mengunjungi 11 negara bagian saja. Berbeda dari teman-teman lain yang sudah mengunjungi 16 bahkan 20 negara bagian. Kriteria berkunjungku sedikit berbeda karena kota atau negara bagian tujuan itu harus memiliki perpustakaan atau toko buku yang bisa disinggahi dan ditilik. Bila tidak ada salah satu kriteria tersebut, aku akan mengabaikannya. Walaupun begitu, aku sudah cukup puas dengan raihanku sekarang. Berikut negara bagian dan kota yang kusinggahi: Phoenix di Arizona (tentu saja karena ini tempat tinggal sementaraku), Austin di negara bagian Texas, San Diego di California, Las Vegas di Nevada, Seattle di Washington, New York City di New York, Jersey City di New Jersey, Washington D.C. di District of Columbia, Baltimore di Maryland, Chicago di Illinois, dan Portland di Oregon.
Setiap negara bagian memiliki cerita tersendiri: ada yang dikunjungi bersama teman, ada yang dikunjungi sendiri, ada yang menginap di rumah nyaman dari AirBnB, ada yang menginap gratis melalui Couchsurfing, kadang melelahkan, lebih banyak menyenangkan. Namun, dari setiap negara bagian yang pernah kukunjungi, ada beberapa poin yang bisa ditarik garis lurus. Negara-negara bagian itu memiliki persamaan entah itu dari faktor pribadi ataupun dari segi sama-sama bagian dari negara adidaya Amerika Serikat.
Aku tidak pernah naik pesawat sampai setelah membeli tiket pesawat dengan uang sendiri untuk liburan ke Padang pada Maret 2017. Itu berarti saat umurku sudah 23 tahun. Setahun berikutnya, aku terbang ke Makassar untuk meliput rangkaian acara Makassar International Writers Festival 2018. Pada saat itu, aku tidak pernah berpikir untuk bepergian menggunakan pesawat lagi. Selain mahalnya harga tiket, kecelakaan yang kerap terjadi membuatku takut untuk bepergian pakai pesawat. Takdir berkata lain: aku lolos beasiswa di Amerika Serikat dengan mengharuskan berada di udara selama lebih dari 20 jam untuk mencapainya. Setelah itu, karena aku begitu terobsesi dengan negara bagian lain di Amerika Serikat, aku yang selalu antusias tidak punya pilihan selain terbang dengan pesawat untuk mengunjungi kota baru di negara bagian yang baru.
Pernah dengar critical eleven? Frasa itu masyhur berkat Ika Natassa yang menggunakannya untuk judul novelnya. Critical eleven dalam dunia penerbangan berarti waktu kritis sebelas menit yang krusial: terdiri atas delapan menit kala lepas landas dan tiga menit kala pendaratan. Pada sebelas menit itu, semua nyawa penumpang bergantung pada pilot yang mengoperasikan pesawat. Tidak hanya perihal pengoperasian pesawat, dilansir dari Kumparan, sebelas menit itu juga digunakan pilot untuk “melakukan komunikasi secara intensif dengan Air Traffic Controller (ATC) untuk mengendalikan pesawat sesuai dengan standar operasi yang berlaku.” Yah, kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana diri ini tidak gemetaran setiap kali terbang dengan pesawat?
2. Tiada tempat tanpa Bahasa Spanyol
“I’m sick of this language,” ujar seorang teman. Dia sadar betul di setiap pengumuman transportasi publik, markah-markah yang terpampang di tempat umum, bahkan pamflet dan buku panduan yang diterbitkan pemerintah semua kata, frasa, kalimat, paragraph yang berbahasa Inggris selalu bersanding dengan Bahasa Spanyol. Aku pun menyadari betul dan sempat sama muaknya dengan temanku itu. Sebelum vakansi winter break, aku sempat berandai-andai kalau di New York City nanti tidak memakai Bahasa Spanyol di transportasi publik. Andaianku itu tentu saja tidak tepat—bahkan di New York City! Setelah itu, aku begitu ingin tahu kenapa Bahasa Spanyol tidak lepas dari Amerika Serikat.
Menurut sejarah, Bahasa Spanyol menjadi salah satu bahasa yang dipakai oleh pendahulu-pendahulu Amerika bagian utara. Orang-orang dari Spanyol tiba di wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat sejak 1493 ketika Columbus pertama tiba di Puerto Rico. Setelah itu, mereka menyebar dan melebur ke seluruh bagian Amerika Serikat. Menurut data yang ditilik dari The Guardian, Amerika Serikat memiliki lebih dari 41 juta penutur asli Bahasa Spanyol dan 11 juta orang lainnya penutur bilingual Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris. Paling banyak dari mereka tinggal di negara bagian California, New Mexico, Texas, dan tentu saja Arizona. Data tersebut juga memastikan bahwa Amerika Serikat memiliki lebih banyak penurut Bahasa Spanyol ketimbang negara Spanyol itu sendiri. Kalau sudah begini, Bahasa Spanyol sudah pasti tidak bisa terlepas dari Amerika Serikat. Sabar-sabar saja ya, temanku!
 |
| Salah satu plang perempatan di Portland (Dokumen Pribadi) |
3. Sudah biasa nama jalan pakai nomor
Di Indonesia, kebanyakan nama jalan menggunakan nama pahlawan—tentu saja, pahlawan di Indonesia kan banyak sekali. Selain untuk menghormati jasa mereka, nama pahlawan pada nama jalan juga digunakan untuk terus diingat oleh masyarakat masa kini. Selain memakai nama pahlawan, nama jalan di Indonesia juga biasanya menggunakan nama-nama buah, nama-nama binatang, dan nama-nama kota atau daerah. Namun, tidak jarang jalan-jalan di Indonesia tidak memiliki nama, terutama di daerah pedesaan yang masih menggunakan RT, RW, dan dusun sebagai penunjuk alamat rumah.
Di Amerika Serikat juga sama kok. Ada jalan-jalan yang memakai nama tokoh mereka; seperti Washington atau Martin Luther King Jr. Akan tetapi cukup sampai di situ. Mereka lebih memilih menggunakan nomor untuk nama jalan. Dari Main Street, 1st Street, 2nd Street, sampai 148th Street atau lebih. Dan ketika menggunakan 148th Street, mereka benar-benar menggunakan bilangan-bilangan sebelumnya sebagai jalan juga—sehingga tidak ada yang mubazir. Sebetulnya, ada nama-nama lain yang kerap digunakan seperti: Abbey, Greenfield, Prince, Queen, York, dan lainnya. Namun, nama-nama itu tidak bisa diklasifikasikan ke kelompok apa pun.
4. Sampah dan gelandangan di mana-mana
Suatu siang, saya dan seorang teman sedang berjalan di trotoar menuju halte bus ketika seseorang di depan kami membuka sebuah bungkusan plastik entah apa dan membuangnya begitu saja. Kami yang sama-sama melihatnya saling tatap heran. Padahal halte bus yang selalu tersedia tempat sampah sudah tampak di depan mata. Apa susahnya menggenggamnya sebentar sebelum memasukkannya ke tempat sampah? Aku pikir semua orang di negara adidaya ini sudah berpikiran maju. Aku pikir mereka akan menyimpan sampahnya di saku baju atau celananya lalu membuangnya setelah menemukan tong sampah. Salah satu bentuk stereotipe yang biasa ditujukan kepada orang-orang di negara maju semacam Amerika Serikat.
Siapa bilang kalau di negara maju seperti Amerika Serikat tidak ada gelandangan dan sampah? Semakin besar kotanya, semakin terlihat bentukannya. Salah satu yang aku ingat adalah di Seattle. Ketika sedang berjalan menyeberang sebuah jembatan, aku iseng menilik ke pinggirannya dan melihat gundukan sampah yang sepertinya seseorang membuangnya di sana secara berkala. Parahnya lagi, di samping gundukan itu ada sebuah tenda hampir roboh yang sepertinya dihuni oleh gelandangan. Saat menumpangi kereta jalur cepat di Portland, aku juga melihat potret yang persis sama dengan di Seattle. Sewaktu musim dingin di New York City, aku melihat seorang gelandangan yang memakai tenda kecil yang cukup menutupi tubuhnya saja.
5. Perpustakaan bau!
Poin ini ada hubungannya dengan poin sebelumnya. Bayangkan ada gelandangan di sebuah kota dan kota tersebut memasuki musim dingin. Gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal akan merasa kedinginan setiap hari dan malamnya. Di manakah tempat mereka bernaung setidaknya sewaktu siang hari? Tentu saja tempat-tempat publik yang gratis dan tertutup. Perpustakaan publik menjadi salah satu tempat favorit. Di perpustakaan mana pun aku berkunjung, tiada yang tidak ada gelandangannya. Dan tiada gelandangan yang tak bau—karena semua sudah tahu bahwa mereka jarang bebersih.
Perpustakaan publik paling bau mungkin di Multnomah County Central Library di Portland. Begitu masuk, aroma tidak sedap langsung menusuk. Mungkin Jati Wesi akan pingsan bila masuk ke dalamnya. Paling bau kedua adalah Clark County Library di Las Vegas. Aroma menyengat dari seseorang yang sedang menyeduh pasta instan dengan keju masih melekat dalam memori. Dan, iya, dia melakukannya di dalam ruang baca perpustakaan. Kadang kesal karena perpustakaan yang harusnya jadi tempat nyaman untuk membaca runtuh gara-gara aroma tidak sedap yang dibawa para gelandangan. Namun, di mana lagi mereka akan bernaung dalam kondisi cuaca yang dingin banget atau panas banget. Sebuah ironi yang bikin elus dada.
6. Setiap kota memiliki setidaknya satu toko buku ikonik
Selain perpustakaan, toko buku menjadi lokasi wajib kunjung setiap datang ke sebuah kota (bila ada dan bila sempat waktunya). Biar aku sebutkan toko buku-toko buku yang kudatangi di Amerika Serikat: Changing Hands Bookstore dan Bookmans di Phoenix, The Elliot Bay Book Company di Seattle, BookPeople di Austin, Strand Book Store di New York City, The Book Cellar di Chicago, dan Powell’s Books di Portland.
Mereka adalah toko buku-toko buku yang direkomendasikan baik oleh warga setempat maupun via Google Maps. Dan sungguh, setiap memasuki toko buku berbeda rasanya juga berbeda. Ada ciri khas tersendiri dari setiap toko buku, padahal buku-buku yang dijual juga sama (alias kumpulan halaman-halaman kertas). Perbedaan yang paling kentara adalah hampir setiap dari mereka memiliki cendera mata yang dijual sendiri: dari tote bag hingga gantungan kunci.
 |
| Salah satu catatan kecil pada salah satu rak di The Elliot Bay Book Company, Seattle (Dokumen Pribadi) |
7. Catatan kecil pada buku-buku di rak
Poin ini yang paling kusuka. Tiada toko buku yang tak memiliki catatan kecil yang terselip di setiap rak, baik itu catatan rekomendasi, pilihan staf dan alasannya, maupun pemberitahuan bahwa buku itu adalah buku baru. Hal ini juga dilakukan di toko buku jaringan besar di Amerika Serikat—Barnes & Noble. Selain sebagai bentuk pemberitahuan, catatan kecil ini juga terkesan lebih humanis. Itu menunjukkan bahwa ada mereka yang peduli dengan buku-buku yang dijual dan pengunjung yang mungkin bingung akan membaca—atau membeli—buku apa. Membaca catatan kecil ini malah menjadi kebiasaanku setiap memasuki toko buku di Amerika Serikat. Sejauh yang kuingat, catatan kecil seperti ini tidak ada di toko buku di Indonesia—terutama yang retail. Tolong beri tahu bila ada toko buku di Indonesia yang menyelipkan catatan kecil di raknya.
Baca juga:
Cerita dari Gurun: Setelah 50 Jam Jadi Sukarelawan
Cerita dari Gurun: Setengah Jalan Lagi

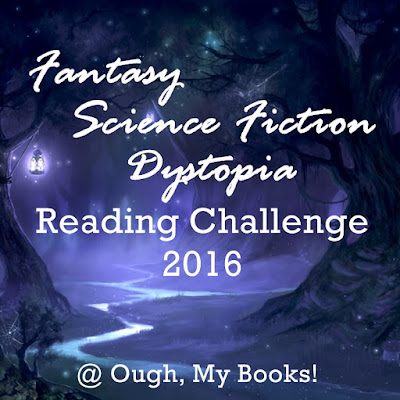

Komentar
Posting Komentar