Penerbit Indie dan Penerbit Mayor Jalan Berbarengan
 |
| Edited by Me |
Saat berada di Jogja beberapa waktu lalu, aku sempat mengobrol dengan teman komunitas yang merupakan salah satu editor penerbitan di sana. Tidak ingat bahasan apa yang kami obrolkan waktu itu, tapi ada satu kepingan obrolan yang masing terngiang dalam benak. Aku bertanya tentang beberapa buku terjemahan dari penerbit-penerbit indie. Sepengetahuanku, beberapa penerbit indie tidak hanya menerbitkan terjemahan klasik yang hak penerjemahannya sudah jadi ranah publik (public domain), tetapi juga buku-buku yang baru belasan tahun lalu diterbitkan di negara asal mereka. Temanku itu mengatakan secara gamblang bahwa kebanyakan dari penerbit indie di Indonesia tidak memikirkan hak penerjemahannya. Mereka hanya terjemahkan dan terbitkan. Bukan lagi rahasia, hal yang sama pun disampaikan oleh Teddy W. Kusuma dalam acara Beranda Sastra #9 Sabtu kemarin.
Intermeso sebelum melanjutkan topik penerbit indie itu. Belakangan ini, aku kerap menayangkan hal-hal yang menurutku penting untuk dibagi melalui Instagram Story. Saat acara Beranda Sastra #9, aku membagikan poster acara dengan catatan tambahan: "kalo nggak baca buku, nulis tentang buku, ya datang ke acara buku". Tak berapa lama, seseorang berkomentar "flat life". Di situ saya tertohok. Saya tahu dia, dia bahkan juga suka membaca. Mungkin itu adalah sikap impulsifnya. Atau mungkin dia bercanda. Banyak pengandaian yang saya pasang untuk mengurungkan rasa benci saya. Tapi, tidak bisa. Saya membalas, "Emang hidup lo nggak flat?"
Saking terpikirkannya pernyataan itu, saya sampai membagikan percakapan itu di Instagram Story. Beberapa teman pembaca meresponsnya. Seorang menimpali, "Kalau saya sih hidupnya round. Saya nggak percaya yang flat-flat. Apalagi flat earth." Sungguh respons yang bikin sedikit tergelak. Teman lain berujar, "Nggak tau sensasinya mungkin yang komentar, Raaf." Yang lain lagi berkata, "Kupikir itu malah seru banget. Beda orang beda kesukaan sih." Sampai pada pernyataan itu, aku diingatkan kembali betapa membaca buku adalah hobi. Sama dengan aku yang tidak hobi makan, rekan kerja saya itu juga tidak terlalu suka membaca. Satu respons terakhir dari seseorang yang menggenapi pernyataan sebelumnya: "balas gini aja, 'If I'm living pursuing things I like and love, how could it be flat?'" Lalu, apa intinya? Aku hanya ingin berbagi pengalaman saat suatu hal yang kamu sukai dinilai "flat life". Jadi, bijak-bijaklah dalam berkomentar.
Kembali ke laptop, mari sejenak cari tahu acara apa yang aku hadiri kemarin. Beranda Sastra #9 adalah salah satu acara yang diadakan oleh Bentara Budaya Jakarta dan mengangkat topik-topik bacaan terutama sastra. Pada September ini, tema yang diangkat adalah "Terbitan Buku Sastra Indie dari Dulu Sampai Nanti". Dihadiri oleh Teddy W. Kusuma, pendiri toko buku indie POST Santa sekaligus penerbit POST Press, dan Septi Ws, editor fiksi dari Penerbit Grasindo, acara kemarin sore dimoderatori oleh Wa Ode Wulan, editor kanal Sastra Jurnal Ruang.
Penerbit indie bisa dibagi ke dalam dua masa. Yaitu sebelum tahun 2010 dan setelah 2010. Pada masa sebelum 2010, penerbit indie masih tergolong lesu. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh anggapan bahwa kualitas buku-buku terbitan indie—dari fisik buku sampai editorial—tidak baik dan tidak menarik. Berbeda dengan masa setelah 2010, ketika penerbit-penerbit indie mulai menggeliat dan semakin banyak. Mereka memiliki alternatif-alternatif yang tidak terjadi pada penerbit mayor. Di antaranya, dalam segi strategi pemasaran. Penjualan buku melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Mereka juga dapat tes pasar terlebih dahulu dengan mencetak buku dengan oplah kecil—bisa hanya 300-500 buku pada kali pertama cetak. Penerbit indie pun memiliki reseller-reseller regional yang punya komunitasnya sendiri nan loyal.
Kata Orang tentang Penerbit Indie
Anggapan bahwa buku-buku terbitan penerbit indie yang tidak berkualitas pun dipatahkan secara berangsur-angsur. Hingga sekarang, banyak karya sastra indie yang mendapatkan nominasi penghargaan di acara perbukuan bergengsi di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan meraih penghargaan tersebut. Baru-baru ini, penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa 2017 mengumumkan sepuluh besar karya terbaiknya. Tiliklah judul-judul yang masuk, sebagian besar di antara daftar tersebut adalah buku-buku terbitan indie. Pada Kategori Fiksi, ada "Bakat Menggonggong" karya Dea Anugrah, "Telumbuk, Dangdut dan Kisah Cinta Yang Keparat" karya Kedung Darma Romansa, "Pagi Yang Miring Ke Kanan" karya Afrizal Malna, dan masih ada beberapa lagi. Bahkan jika diselisik lebih jeli, hanya satu buku pada Kategori Puisi yang merupakan terbitan penerbit mayor yaitu "Penyair Revolusioner" karya Deddy Arsyadi terbitan Penerbit Grasindo. Sisanya? Penerbit indie. Jadi, masih menyangkal soal kualitas?
Ada satu gagasan menarik yang diajukan oleh Wulan. Ia menyatakan bahwa kebanyakan penulis ingin menerbitkan buku melalui jalur penerbit mayor. Teddy menyanggahnya, mengatakan bahwa akan berbeda bila karya penulis itu diterbitkan secara indie. Pertimbangannya adalah jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit indie dalam setahun tidak banyak sehingga membuat proses pemasarannya lebih panjang dan fokus. Bisa saja dengan pemasaran seperti itu, buku-buku tersebut bisa habis dalam satu hingga dua tahun. Atau lebih bagus jika dicetak ulang. Selain itu, penulis akan memilih kedekatan dengan editornya. Ada unsur personal ketika penulis ingin menerbitkan karyanya melalui penerbit mayor atau penerbit indie. Seperti M. Aan Mansyur yang menyebutkan karya-karyanya sebagai "karya kami" atau hasil kolaborasi antara dirinya dengan sang editor.
Perihal Penerbit Mayor
Bagaimana dengan penerbit mayor sendiri? Septi menjelaskan bahwa sebagai bagian dari korporasi, penerbit mayor tentu mempertimbangkan profit dari buku-buku yang diterbitkannya. Bisa dibilang, penerbit mayor hanya menerbitkan buku-buku yang memiliki prospek surplus. Maka dari itu, buku-buku yang dilahirkan adalah buku-buku bagi pembaca arus utama. Fiksi adalah yang paling terlihat, bila digolongkan lagi, genre romansa adalah yang paling paling terlihat. Hadirnya penerbit indie memberikan alternatif bacaan bagi para pembaca yang bukan golongan arus utama. Karya-karya klasik dan sastra eksperimental digodog dan dikemas menarik untuk menyemarakkan pilihan bacaan bagi para pencinta buku. Dengan kata lain, penerbit indie bisa melengkapi apa yang tidak diberikan oleh penerbit mayor. Septi bahkan memiliki keinginan untuk membikin kerja sama antara penerbit indie dengan penerbit mayor.
"Penerbit indie akan gagal jika ingin menjadi penerbit mayor," ujar Teddy. Ia mencontohkannya dengan oplah cetak. Akan tidak berjalan baik ketika penerbit indie mencetak buku sebanyak oplah cetak penerbit mayor yang ribuan eksemplar itu. Bila tetap berkeras untuk melakukannya tanpa mempertimbangkan banyak hal, mereka akan menuju kegagalannya.
Penerbit Indie dan Penerbit Mayor, Nanti
Pada kesempatan terakhir, Teddy mengatakan bahwa kesempatan penerbit indie akan besar ke depannya. Stamina yang kuat harus dimiliki para pelaku penerbitan indie, karena itu modal utama. Yang tak kalah penting adalah kesempatan membangun ekosistem secara kreatif yang bikin pembaca merayakan buku-buku. Misalnya, MocoSik Festival di Jogja yang mengharuskan pengunjung yang datang membeli buku-buku terbitan indie sebagai tiket masuk. Acara tersebut secara langsung membentuk komunitas dan ekosistem baru. "Kalau penerbit indie tetap bertahan untuk tidak terlalu besar, pembacanya akan makin loyal. Akan ada pembaca seperti pada New Directions yang akan membeli buku apa saja yang diterbitkannya," pungkasnya.
Jadi, apakah ada perang dingin antara penerbit indie dan penerbit mayor? Tentu tidak. Seperti yang Septi bilang, ia tidak khawatir dengan maraknya penerbit indie yang bermunculan. "Penerbit indie dan penerbit mayor bisa jalan berbarengan. Juga saling melengkapi," ujarnya.
Soal hak terjemahan yang seringkali diabaikan penerbit indie, mengambil dari tulisan Teddy, itu termasuk beberapa persoalan yang masih jadi pekerjaan rumah. Persoalan lainnya adalah kurangnya penulis perempuan yang diterbitkan penerbit indie dan beberapa penerbit yang menangani royalti penulis dengan buruk. Sembari mengatasi persoalan-persoalan tersebut, penerbit indie dan penerbit mayor dapat saling memberikan andil dalam penyediaan ragam jenis bacaan yang bagus untuk penikmat bacaan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
***
Intermeso sebelum melanjutkan topik penerbit indie itu. Belakangan ini, aku kerap menayangkan hal-hal yang menurutku penting untuk dibagi melalui Instagram Story. Saat acara Beranda Sastra #9, aku membagikan poster acara dengan catatan tambahan: "kalo nggak baca buku, nulis tentang buku, ya datang ke acara buku". Tak berapa lama, seseorang berkomentar "flat life". Di situ saya tertohok. Saya tahu dia, dia bahkan juga suka membaca. Mungkin itu adalah sikap impulsifnya. Atau mungkin dia bercanda. Banyak pengandaian yang saya pasang untuk mengurungkan rasa benci saya. Tapi, tidak bisa. Saya membalas, "Emang hidup lo nggak flat?"
Saking terpikirkannya pernyataan itu, saya sampai membagikan percakapan itu di Instagram Story. Beberapa teman pembaca meresponsnya. Seorang menimpali, "Kalau saya sih hidupnya round. Saya nggak percaya yang flat-flat. Apalagi flat earth." Sungguh respons yang bikin sedikit tergelak. Teman lain berujar, "Nggak tau sensasinya mungkin yang komentar, Raaf." Yang lain lagi berkata, "Kupikir itu malah seru banget. Beda orang beda kesukaan sih." Sampai pada pernyataan itu, aku diingatkan kembali betapa membaca buku adalah hobi. Sama dengan aku yang tidak hobi makan, rekan kerja saya itu juga tidak terlalu suka membaca. Satu respons terakhir dari seseorang yang menggenapi pernyataan sebelumnya: "balas gini aja, 'If I'm living pursuing things I like and love, how could it be flat?'" Lalu, apa intinya? Aku hanya ingin berbagi pengalaman saat suatu hal yang kamu sukai dinilai "flat life". Jadi, bijak-bijaklah dalam berkomentar.
Kembali ke laptop, mari sejenak cari tahu acara apa yang aku hadiri kemarin. Beranda Sastra #9 adalah salah satu acara yang diadakan oleh Bentara Budaya Jakarta dan mengangkat topik-topik bacaan terutama sastra. Pada September ini, tema yang diangkat adalah "Terbitan Buku Sastra Indie dari Dulu Sampai Nanti". Dihadiri oleh Teddy W. Kusuma, pendiri toko buku indie POST Santa sekaligus penerbit POST Press, dan Septi Ws, editor fiksi dari Penerbit Grasindo, acara kemarin sore dimoderatori oleh Wa Ode Wulan, editor kanal Sastra Jurnal Ruang.
Penerbit indie bisa dibagi ke dalam dua masa. Yaitu sebelum tahun 2010 dan setelah 2010. Pada masa sebelum 2010, penerbit indie masih tergolong lesu. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh anggapan bahwa kualitas buku-buku terbitan indie—dari fisik buku sampai editorial—tidak baik dan tidak menarik. Berbeda dengan masa setelah 2010, ketika penerbit-penerbit indie mulai menggeliat dan semakin banyak. Mereka memiliki alternatif-alternatif yang tidak terjadi pada penerbit mayor. Di antaranya, dalam segi strategi pemasaran. Penjualan buku melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Mereka juga dapat tes pasar terlebih dahulu dengan mencetak buku dengan oplah kecil—bisa hanya 300-500 buku pada kali pertama cetak. Penerbit indie pun memiliki reseller-reseller regional yang punya komunitasnya sendiri nan loyal.
Kata Orang tentang Penerbit Indie
Anggapan bahwa buku-buku terbitan penerbit indie yang tidak berkualitas pun dipatahkan secara berangsur-angsur. Hingga sekarang, banyak karya sastra indie yang mendapatkan nominasi penghargaan di acara perbukuan bergengsi di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan meraih penghargaan tersebut. Baru-baru ini, penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa 2017 mengumumkan sepuluh besar karya terbaiknya. Tiliklah judul-judul yang masuk, sebagian besar di antara daftar tersebut adalah buku-buku terbitan indie. Pada Kategori Fiksi, ada "Bakat Menggonggong" karya Dea Anugrah, "Telumbuk, Dangdut dan Kisah Cinta Yang Keparat" karya Kedung Darma Romansa, "Pagi Yang Miring Ke Kanan" karya Afrizal Malna, dan masih ada beberapa lagi. Bahkan jika diselisik lebih jeli, hanya satu buku pada Kategori Puisi yang merupakan terbitan penerbit mayor yaitu "Penyair Revolusioner" karya Deddy Arsyadi terbitan Penerbit Grasindo. Sisanya? Penerbit indie. Jadi, masih menyangkal soal kualitas?
Ada satu gagasan menarik yang diajukan oleh Wulan. Ia menyatakan bahwa kebanyakan penulis ingin menerbitkan buku melalui jalur penerbit mayor. Teddy menyanggahnya, mengatakan bahwa akan berbeda bila karya penulis itu diterbitkan secara indie. Pertimbangannya adalah jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit indie dalam setahun tidak banyak sehingga membuat proses pemasarannya lebih panjang dan fokus. Bisa saja dengan pemasaran seperti itu, buku-buku tersebut bisa habis dalam satu hingga dua tahun. Atau lebih bagus jika dicetak ulang. Selain itu, penulis akan memilih kedekatan dengan editornya. Ada unsur personal ketika penulis ingin menerbitkan karyanya melalui penerbit mayor atau penerbit indie. Seperti M. Aan Mansyur yang menyebutkan karya-karyanya sebagai "karya kami" atau hasil kolaborasi antara dirinya dengan sang editor.
Perihal Penerbit Mayor
Bagaimana dengan penerbit mayor sendiri? Septi menjelaskan bahwa sebagai bagian dari korporasi, penerbit mayor tentu mempertimbangkan profit dari buku-buku yang diterbitkannya. Bisa dibilang, penerbit mayor hanya menerbitkan buku-buku yang memiliki prospek surplus. Maka dari itu, buku-buku yang dilahirkan adalah buku-buku bagi pembaca arus utama. Fiksi adalah yang paling terlihat, bila digolongkan lagi, genre romansa adalah yang paling paling terlihat. Hadirnya penerbit indie memberikan alternatif bacaan bagi para pembaca yang bukan golongan arus utama. Karya-karya klasik dan sastra eksperimental digodog dan dikemas menarik untuk menyemarakkan pilihan bacaan bagi para pencinta buku. Dengan kata lain, penerbit indie bisa melengkapi apa yang tidak diberikan oleh penerbit mayor. Septi bahkan memiliki keinginan untuk membikin kerja sama antara penerbit indie dengan penerbit mayor.
"Penerbit indie akan gagal jika ingin menjadi penerbit mayor," ujar Teddy. Ia mencontohkannya dengan oplah cetak. Akan tidak berjalan baik ketika penerbit indie mencetak buku sebanyak oplah cetak penerbit mayor yang ribuan eksemplar itu. Bila tetap berkeras untuk melakukannya tanpa mempertimbangkan banyak hal, mereka akan menuju kegagalannya.
 |
| Para Panelis (Sumber Gambar: @bentaramuda) |
Penerbit Indie dan Penerbit Mayor, Nanti
Pada kesempatan terakhir, Teddy mengatakan bahwa kesempatan penerbit indie akan besar ke depannya. Stamina yang kuat harus dimiliki para pelaku penerbitan indie, karena itu modal utama. Yang tak kalah penting adalah kesempatan membangun ekosistem secara kreatif yang bikin pembaca merayakan buku-buku. Misalnya, MocoSik Festival di Jogja yang mengharuskan pengunjung yang datang membeli buku-buku terbitan indie sebagai tiket masuk. Acara tersebut secara langsung membentuk komunitas dan ekosistem baru. "Kalau penerbit indie tetap bertahan untuk tidak terlalu besar, pembacanya akan makin loyal. Akan ada pembaca seperti pada New Directions yang akan membeli buku apa saja yang diterbitkannya," pungkasnya.
Jadi, apakah ada perang dingin antara penerbit indie dan penerbit mayor? Tentu tidak. Seperti yang Septi bilang, ia tidak khawatir dengan maraknya penerbit indie yang bermunculan. "Penerbit indie dan penerbit mayor bisa jalan berbarengan. Juga saling melengkapi," ujarnya.
Soal hak terjemahan yang seringkali diabaikan penerbit indie, mengambil dari tulisan Teddy, itu termasuk beberapa persoalan yang masih jadi pekerjaan rumah. Persoalan lainnya adalah kurangnya penulis perempuan yang diterbitkan penerbit indie dan beberapa penerbit yang menangani royalti penulis dengan buruk. Sembari mengatasi persoalan-persoalan tersebut, penerbit indie dan penerbit mayor dapat saling memberikan andil dalam penyediaan ragam jenis bacaan yang bagus untuk penikmat bacaan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.


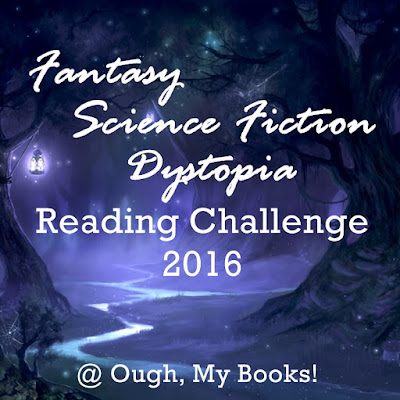

klo kayak rumah kertas itu terbitan indie juga gk sih raaf??? aku masih sering bingung bedain buku terbitan indie sama mayor... haha... masih newbie... #tsaah :D
BalasHapusperbedaan yang paling kentara: penerbit indie melakukan semua proses penerbitan dari kurasi naskah sampai penjualan secara sendiri atau independen, sedangkan untuk penerbit mayor mereka hanya mengkurasi naskah lalu pendistribusian sampai penjualan ada yang mengurus lagi.
Hapus